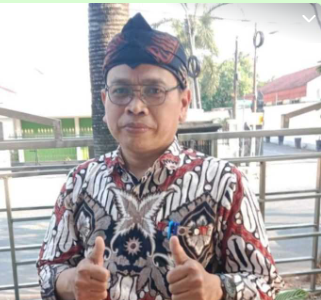MEMANGGIL.CO - Hari Pendidikan telah berlalu, tetapi hingga tulisan ini diangkat masih saja ganjalan di alam pikir penulis, tahun ini “2025”, Hari Pendidikan Nasional mengangkat tema yang tampak hebat dan menjanjikan untuk perbaikan di dunia pendidikan tanah air.
Tema Hari Pendidikan Nasioanl tahun 2025 adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” tema yang penuh harapan ini kini berhadapan dengan kenyataan sosial yang tak kalah keras, degradasi nilai dalam dunia pendidikan, yang tidak hanya melanda murid, tetapi juga guru.
Semua yang kita saksikan saat ini bukan lagi sebatas kelalaian individu, gejala sistemik dari kebingungan nilai di tengah gempuran digitalisasi menjadi penyebab utama. Di satu sisi, media sosial menawarkan peluang kolaborasi dan kreativitas dan menjanjikan nilai ekonomi disamping kepuasan syahwati. Di sisi lain, ia menjadi ladang subur bagi narsisme dan pelarian identitas. Ketika guru mulai berlomba menciptakan konten viral, dan sebagian justru menjual sisi pribadi yang tak patut ditampilkan di ruang publik, maka kita harus bertanya, apakah pendidikan masih menjadi panggilan moral atau telah berubah menjadi ajang pencitraan?
Muncullah fenomena seperti Bu Guru Salsa, simbol dari guru yang lebih sibuk berjoget demi konten viral ketimbang mendidik dengan keteladanan, ditiru murid-murid yang tumbuh tanpa filter moral dalam budaya digital serba instan. Ketika guru kehilangan marwah dan murid kehilangan arah, muncullah generasi “kaum tulang lunak” . Istilah yang mencerminkan generasi yang rapuh secara karakter, lentur pada tren, dan miskin daya tahan terhadap nilai. Anak-anak ini meniru bukan karena hormat, melainkan karena bingung mencari figur panutan. Ditambah dengan kebebasan berekspresi yang tak disertai pendidikan etika digital, mereka merasa sah saja memaki guru lewat media sosial, mengolok-olok otoritas, dan mengaburkan batas antara kebebasan dan kebebalan.
Di titik ini, peran guru mengalami pergeseran yang mengkhawatirkan. Dulu, guru adalah simbol kewibawaan, keteladanan, dan penjaga nilai. Kini, sebagian guru justru mengaburkan garis batas antara profesi dan hiburan. Konten senam lemah gemulai, gurauan berlebihan, atau bahkan penampilan vulgar di media sosial menimbulkan bias identitas. Anak didik yang semestinya belajar tentang integritas, justru dijejali gambaran bahwa menjadi guru bukan lagi soal mendidik, tapi soal tampil memikat. Guru harus cantik, guru harus gantheng, guru harus berbibir merah merona, guru harus dan lain-lainnya.
Di sinilah kita melihat krisis yang lebih dalam, krisis otoritas moral. Ketika guru kehilangan marwahnya, dan murid kehilangan arah, maka pendidikan bukan lagi proses transformasi, tapi sekadar tontonan sosial. Lebih buruk lagi, kita mulai terbiasa dengan hal-hal yang salah. Konten absurd dari pendidik tak lagi dikecam, tapi justru dirayakan. Sementara kritik dari murid terhadap guru bukan lagi disampaikan dalam ruang diskusi, tapi lewat video sindiran dan komentar kasar.
Apakah ini wujud dari “partisipasi semesta” yang kita harapkan?
Tentu jawabannya jelas “tidak“. Partisipasi semesta dalam pendidikan semestinya mengandung kesadaran kolektif untuk menjaga nilai, bukan merayakan kelonggaran etika. Partisipasi semesta dalam konteks pendidikan memang bukan hanya soal kehadiran atau keterlibatan secara simbolis, apalagi dalam bentuk konten-konten negatif atau viralitas yang sesaat. Pendidikan adalah proses jangka panjang yang melibatkan semua elemen bangsa—orang tua, guru, pemerintah, media, hingga dunia usaha—dalam mencetak generasi berkarakter dan berperadaban..
Oleh karena itu pada Hari Pendidikan Nasional 2025 ini, kita justru dihadapkan pada ujian berat, mampu atau tidak kita menegakkan kembali martabat pendidikan di tengah gelombang distraksi digital? Mampukah guru kembali menjadi pelita, bukan penghibur? Mampukah murid kembali dididik menjadi manusia utuh, bukan hanya pengguna konten? Jika tidak, maka yang terjadi bukan partisipasi semesta, tapi disorientasi semesta. Pendidikan yang mestinya memerdekakan, justru terjerat dalam budaya instan dan impresi semu.
Sudah waktunya kita bersikap. Pendidikan yang bermutu hanya bisa lahir dari partisipasi yang berakar pada nilai, bukan pada gimmick. Dan jika kita benar-benar mencintai masa depan negeri ini, kita harus memulainya hari ini, dengan keberanian untuk berkata cukup pada semua yang menodai makna pendidikan.
Penulis: Sekretaris Majelis Dikdasmen & PNF PDM Bojonegoro, Suprapto